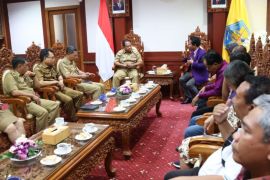Denpasar (ANTARA) - Di Bali ada musisi, penyanyi, pencipta lagu, dan pegiat media sosial, yakni I Gede Ari Astina alias Jerinx atau JRX, yang akhirnya divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Denpasar karena "suara" tentang COVID-19.
Drummer grup musik rock Superman Is Dead (SID) alias Jerinx SID itu akhirnya divonis bersalah dalam kasus ujaran kebencian, bukan karena tidak percaya COVID-19, melainkan karena ujaran "IDI Kacung WHO".
Lain di jalanan, lain pula di gedung parlemen. Ada anggota DPR Komisi IX dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning yang membuat pernyataan kontroversial tentang vaksinasi COVID-19 dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI , Selasa (12/1).
Sontak, jagat maya pun menggelegar dengan video politikus yang akrab disapa Mbak Ning itu pada tautan/link https://www.vlix.id/video/news/86725-ribka-tjiptaning-tolak-vaksin-jangan-bisniskan-covid-19 karena viral dalam selang sehari menjelang vaksinasi COVID-19 perdana oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (13/1).
Bedanya, Jerinx SID yang kelahiran Kuta, Kabupaten Badung, Bali, pada tanggal 10 Februari 1977 itu divonis dengan hukuman 1 tahun 2 bulan penjara ditambah denda Rp10 juta di PN Denpasar (19-11-2020) karena menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu.
Namun, Mbak Ning yang juga tidak percaya COVID-19 itu hanya sebatas menjadi gosip di jagat maya. "Kalau persoalan vaksin saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih. Misalnya hidup di DKI Jakarta semua anak cucu saya dapat sanksi Rp5 juta mending saya bayar," ujar Mbak Ning, dalam rapat kerja tersebut.
Dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM Penny Lukito, dan Direktur PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir di Senayan itu, Mbak Ning dengan tegas menolak untuk divaksin COVID-19 dan memilih untuk membayar denda berapa pun besarnya.
"Saya yang pertama bilang saya yang pertama menolak vaksin. Kalau dipaksa, pelanggaran HAM tidak boleh memaksa begitu," kata politikus yang ada dalam Komisi IX DPR yang sebelumnya justru mengusulkan vaksinasi COVID-19 diberikan kepada pejabat untuk pertama kalinya itu.
Baca juga: Jubir COVID-19 : Pro-kontra vaksin akibat medsos
Mbak Ning mendasarkan keraguan pada vaksin COVID-19 dengan merujuk pada pengalaman pemberian sejumlah vaksin lainnya, yang justru membuat orang lumpuh hingga meninggal dunia. Misalnya, vaksin antipolio membuat sejumlah orang lumpuh di Sukabumi dan vaksin kaki gajah di Majalaya yang menyebabkan 12 orang meninggal dunia.
Tidak hanya menolak vaksin, dia juga mengeluarkan pernyataan keras lainnya dengan menyebut komersialisasi atau bisnis tes swab COVID-19 di rumah sakit karena tarif tes swab dipatok dengan harga yang berbeda pada sejumlah rumah sakit, mulai Rp900 ribu hingga Rp3,5 juta.
Mbak Ning mengaku khawatir komersialisasi juga berlanjut pada vaksin COVID-19. Namun, tidak hanya menolak vaksinasi, atau menyebut komersialisasi, Mbak Ning juga merembet ke latar belakang Menkes yang sarjana teknik fisika nuklir.
Penolakan vaksinasi oleh Ribka Tjiptaning itu ditanggapi Relawan Penanganan COVID-19 Tirta Mandira Hudhi alias dr. Tirta, yang mempertanyakan perubahan sikap Ribka Tjiptaning karena sejak awal yang mengusulkan pejabat divaksinasi COVID-19 adalah Komisi IX DPR.
"Gak perlu sampean divaksin duluan. Saya, duluan. Saya juga gak setuju vaksin diwajibkan. Harusnya wakil rakyat dan nakes yang jadi contoh edukasi. Oke, saya akan mencatat ini bila kelak Ribka meminta vaksin apa pun, bahkan vaksin merah putih," katanya dalam akun Instagramnya, Rabu (13/1).
Ia mempertanyakan ke mana Ribka selama 9 bulan terakhir saat pemerintah gencar-gencarnya mencari solusi dalam penanganan COVID-19.
"Jika Anda tolak, ke mana selama 9 bulan terakhir? Saat penanganan COVID? Muncul pas APD, obat, sama vaksin. Kok, pas bulan Juli gak ikut kritik vaksin, eh, begitu dah keluar EUA, baru komentar?" katanya.
Baca juga: 2,9 juta penerima vaksin COVID-19 di Bali dibagi lima kelompok
Penolakan dan Euforia
Agaknya penolakan politis atau penolakan nonpolitis (tidak percaya virus) itu agaknya perlu mempertimbangkan fakta virus COVID-19 itu yang kini justru terus meningkat, bahkan secara nasional tercatat sudah di atas kisaran 10.000 orang Indonesia yang terpapar dalam sehari.
Soal penolakan tidak percaya adanya virus itu agaknya masih ada sesuatu yang tidak terlihat (kasatmata) karena ukuran materialnya yang amat kecil namun diyakini adanya, seperti udara atau kematian yang tidak terlihat, namun manusia tidak bisa hidup tanpa udara atau mengelak dari mati.
Soal penolakan vaksin yang sifatnya politis atau teknis medis juga perlu dikembalikan kepada ahlinya, apalagi BPOM sudah terlibat dalam uji coba sebanyak tiga kali dan MUI pun terlibat dalam uji kehalalan.
Nah, apakah fakta korban yang terus meningkat harus dikalahkan dengan penolakan politis dan soal 'tidak percaya' itu? Ya, secara teknis manajerial agaknya Indonesia perlu 'mengejar waktu' dengan angka korban dan kematian akibat COVID-19 daripada 'berhenti' untuk melayani penolakan itu.
"Umumnya, orang kini terpengaruh medsos. Harus lebih sabar menghadapi, padahal mereka berpendidikan sarjana. Memang tidak mudah, banyak alasan untuk membantah," kata mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam catatan DI's Way, Kamis (7/1).
Baca juga: Penyebar hoaks vaksinasi tewaskan Kasdim 0817 diburu Polres Gresik
Bahkan, Dahlan Iskan yang juga mantan bos Harian Jawa Pos itu mengaku sudah menjelaskan satu per satu pada setiap keraguan, bahkan telak. "Tapi satu persoalan selesai dan tak terbantahkan, maka keraguan kedua pun muncul, dijelaskan lagi, dan terus muncul keraguan lain, terus begitu," katanya.
Ending keraguan itu tak jarang dibumbui alasan ayat-ayat Alquran. "Sebagai lulusan madrasah aliah, saya bisa saja menjawab. Akan tetapi, kalau perdebatan soal ayat-ayat Alquran, diam itu lebih baik daripada banyak menguras energi," katanya.
Solusinya, keputusan harus diambil pemerintah. "Soal lingkaran medsos itu, bukan hanya problem Indonesia. Itu problem seluruh dunia, sampai Paus di Vatikan pun dipaksa harus mengeluarkan fatwa 'halal' untuk vaksin," katanya.
Bahkan, di Amerika pun sampai terjadi sabotase vaksin yang justru dilakukan apoteker dengan pengalaman 23 tahun menjadi apoteker. Akhirnya, malam tahun baru 2021, apoteker Stephen Brandenburg pun ditangkap. Dia juga dipecat dari rumah sakit, tempatnya bekerja.
Baca juga: Hoaks, Moeldoko sebut Jokowi pakai vaksin berbeda
"Kejadian itu diketahui teknisi rumah sakit itu. Ia mengaku dengan sengaja mengeluarkan vaksin dari tempat penyimpanan pada malam Natal agar rusak. Brandenburg tidak percaya vaksin itu aman. Alasannya, bisa merusak DNA pemakainya, padahal penjelasan ilmiah sudah disebarluaskan bahwa vaksin tidak akan merusak DNA manusia," katanya.
Begitulah di negara semaju Amerika pun ada yang antivaksin buatan Amerika, sedang yang antivaksin Tiongkok juga lebih banyak, sampai membawa-bawa kitab suci. "Yang seperti itu membuat energi habis untuk mengurusnya, padahal pandemi ini harus selesai, apalagi tidak ditemukan cara lain untuk mengatasi, kita berpacu dengan waktu dan nyawa," katanya.
Ya, soal teknis manajerial 'mengejar waktu' dengan angka korban dan kematian itu, Presiden Joko Widodo pun memesan 329 juta dosis vaksin COVID-19 dari Sinovac, Tiongkok (125 juta lebih), Pfizer, Jerman-AS (50 juta), Novavax, AS-Kanada (50 juta), Covax GAVI--kerja sama multilateral WHO-Aliansi Vaksin Dunia/GAVI oleh 171 negara--(54 juta), dan AstraZeneca, Inggris (50 juta), sedangkan Vaksin Merah Putih, produk RI masih akhir Maret atau awal April 2021.
"Vaksin COVID-19 inilah yang lama kita tunggu-tunggu dan baru disuntikkan setelah BPOM mengeluarkan izin penggunaan darurat, dan Majelis Ulama Indonesia menyatakan suci dan halal untuk digunakan," kata Presiden melalui akun Instagram miliknya, Rabu (13/1).
Baca juga: Ketua MPR divaksin bentuk dukung pemerintah atasi COVID-19
Namun, vaksinasi COVID-19 juga harus dijaga agar tidak memunculkan euforia bahwa dengan vaksin berarti sudah aman karena proses terbentuknya sistem kekebalan (imunitas) itu tidak langsung jadi.
Dengan demikian, protokol kesehatan tetap harus jalan, bahkan jika perlu melalui sanksi yang terukur karena imbauan atau denda saja masih mungkin diremehkan, apalagi infodemik melalui medsos juga bertebaran.